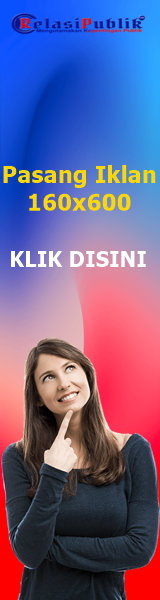sumbar.relasipublik.com // Lubuk Basung
Alih-alih menjadi program yang membawa senyum di wajah anak-anak sekolah, inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG) justru menyisakan luka di Lubuk Basung. Sebanyak 86 orang diduga keracunan usai menyantap hidangan MBG, Rabu (1/10) Angka itu tidak berhenti di situ—hingga Kamis (2/10), jumlah korban terus meningkat hingga menyentuh seratus orang.
Mereka bukan sekadar statistik. Di balik data resmi Dinas Kominfo Agam—6 guru, 2 orang tua murid, 57 pelajar, serta puluhan lainnya yang masih diverifikasi—ada wajah-wajah pucat yang mestinya pulang dengan tawa, kini berakhir di ruang perawatan. Ada guru yang biasanya berdiri di depan kelas dengan penuh semangat, kini terbaring lemah dengan selang infus menusuk tangan.
Gejala yang seragam—mual, pusing, sakit perut, hingga muntah—menjadi cerita kolektif dari ruang-ruang rawat. Tragedi ini bukan sekadar soal kelalaian teknis, tapi soal hilangnya rasa aman pada sebuah program yang mestinya memberi kebaikan.
Niat Baik yang Belum Siap
Program makan gratis sejatinya lahir dari semangat kepedulian. Tapi musibah ini menyodorkan satu pertanyaan mendasar: apa artinya “bergizi” jika justru menghadirkan penyakit, dan apa makna “gratis” bila harus ditebus dengan rasa sakit serta trauma?
Fenomena di Agam hanyalah satu potret dari rangkaian kasus serupa di berbagai daerah Indonesia. Dari Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Sulawesi, kisahnya sama: puluhan anak terkapar setelah menikmati makanan yang seharusnya menyehatkan. Apakah ini harga yang pantas dibayar demi sebuah kebanggaan program?
Pengakuan dan Tindakan Cepat
Bupati Agam Benni Warlis menetapkan kasus ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Pemerintah daerah disebut bergerak cepat—menghentikan sementara dapur MBG yang diduga menjadi sumber keracunan, mengirim sampel makanan untuk pemeriksaan laboratorium, serta memastikan korban mendapat perawatan medis.
“Keselamatan masyarakat adalah prioritas. Kita tidak boleh main-main dalam urusan pangan, apalagi untuk anak-anak kita,” tegas Benni.
Namun di luar langkah cepat itu, ada pekerjaan rumah yang jauh lebih besar: memperbaiki sistem dari hulu hingga hilir. Mulai dari dapur pengolahan, standar higienitas, rantai distribusi, hingga pengawasan lapangan. Karena satu celah saja dalam rantai itu, bisa berujung pada tragedi massal.
Tanggung Jawab di Balik Piring Nasi
Bagi orang tua, setiap piring nasi di sekolah bukan sekadar santapan—itu adalah titipan kepercayaan kepada negara. Saat kepercayaan itu retak karena keracunan massal, wajar jika publik menuntut pemerintah menata ulang dengan hati-hati, bahkan jika perlu menghentikan program sementara.
Makanan semestinya menghadirkan tenaga, bukan derita. Seharusnya menjadi ingatan manis masa sekolah, bukan trauma yang membekas. Karena pada akhirnya, program makan gratis tidak akan pernah berarti jika yang tertinggal hanya pahitnya luka di ingatan anak-anak bangsa(d13)