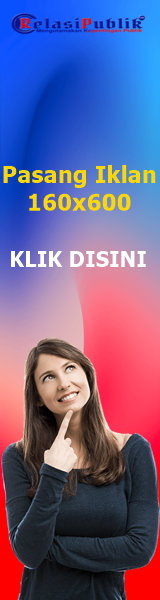Oleh: SISCA OKTRI SANTI, S.S., M.Li.
Wisuda selalu dibayangkan sebagai momen puncak pencapaian akademik. Toga dikenakan, nama dipanggil, tepuk tangan menggema. Namun di balik seremoni yang tampak khidmat itu, ada sebagian mahasiswa yang berdiri dengan tubuh bergetar, menahan sesuatu yang tidak terlihat oleh kamera, tidak terdengar oleh mikrofon, tetapi sangat nyata di dalam diri mereka.
Ada seorang anak perempuan yang saat namanya dipanggil, justru gemetar hebat. Bukan karena haru. Melainkan karena setelah namanya, digaungkan nama bapaknya — sosok yang dalam ingatannya bukan figur pelindung, melainkan sumber trauma. Masa lalu yang kelam. Pahit. Dipenuhi pencabulan yang tak pernah sembuh sepenuhnya. Pada detik itu, wisuda tidak lagi menjadi perayaan. Ia berubah menjadi panggung tempat luka lama dipanggil ulang secara paksa.
Pengalaman ini bukan cerita tunggal. Beberapa waktu lalu, sebuah unggahan di Instagram dari akun *Iiiffyaa._ m* menyuarakan hal yang sama dengan cara yang sangat jujur. Dalam video wisudanya, ia menuliskan kalimat sederhana namun menyayat: “_Kalian ga akan tau rasanya wisuda dengan keluarga berantakan itu lebih sakit, apalagi yg dipanggil pas wisuda nama ayah sedangkan yg berjuang hanya ibu_ 🙂.” Kalimat ini merepresentasikan ribuan suara lain yang selama ini terdiam.
Kampus sering menganggap penyebutan “_anak dari Bapak_…” sebagai formalitas. Tradisi. Tata protokol yang dianggap netral dan wajar. Namun anggapan ini keliru. Dalam kajian linguistik, bahasa tidak pernah netral. Bahasa selalu membawa beban makna, ideologi, dan pengalaman. Ia tidak hanya menyebut, tetapi juga membentuk realitas sosial dan psikis.
Secara linguistik, penyebutan nama orang tua dalam prosesi wisuda adalah tindak tutur institusional. Ia bukan sekadar rangkaian kata, melainkan tindakan simbolik yang memberi legitimasi: siapa yang diakui, siapa yang dihapus, siapa yang dipusatkan, dan siapa yang disisihkan.
Ketika kampus secara otomatis menyebut nama ayah, kampus sedang mereproduksi satu asumsi besar: bahwa ayah selalu hadir, layak, dan menjadi pusat identitas anak. Padahal realitas hidup mahasiswa sangat beragam. Tidak semua ayah hadir sebagai figur aman. Tidak semua ayah hadir sama sekali.
Ada mahasiswa yang tidak pernah bertemu bapaknya. Ada yang ditinggalkan sejak lahir. Ada yang tumbuh besar hanya bersama ibu yang berjuang sendirian. Ada pula yang hidup dengan luka batin mendalam akibat kekerasan fisik, psikologis, bahkan seksual yang dilakukan oleh figur ayah. Namun sistem pendidikan kita berjalan seolah semua keluarga adalah keluarga utuh yang harmonis.
Ada pula kasus anak lelaki yang dengan tegas menolak namanya dipanggil bersama nama bapaknya saat wisuda. Bukan karena benci tanpa sebab, tetapi karena bapaknya tidak pernah bertanggung jawab — tidak hadir secara emosional, tidak hadir secara ekonomi, dan tidak hadir dalam perjalanan hidupnya. Baginya, penyebutan nama bapak bukan bentuk penghormatan, melainkan pengingkaran atas perjuangan ibunya dan dirinya sendiri.
Sering kali, penolakan seperti ini dibenturkan dengan kalimat klise: “Tanpa bapak, anak tidak akan ada.” Pernyataan ini terdengar biologis, tetapi egois secara moral. Anak tidak pernah meminta dilahirkan ke dunia dalam keadaan diabaikan. Anak tidak memilih ayah yang tidak bertanggung jawab. Maka menjadikan fakta biologis sebagai alat legitimasi simbolik adalah bentuk kekerasan wacana yang lain.
Di sinilah bahasa institusi berubah menjadi kekerasan simbolik. Tanpa menyentuh tubuh, tanpa suara kasar, bahasa mampu melukai psikis. Ketika nama yang menyimpan trauma dipanggil di ruang publik, mahasiswa dipaksa menelan ulang kepahitan yang seharusnya tidak lagi menjadi bagian dari pencapaian akademiknya.
Ironisnya, dalam banyak kasus, justru ibu yang memikul seluruh beban kehidupan. Ibu yang menghitung biaya pampers. Ibu yang mencari uang untuk susu. Ibu yang begadang saat anak sakit. Ibu yang membayar biaya sekolah, biaya kuliah, dan segala biaya tak terduga yang datang tanpa aba-aba. Ibu yang bertahan ketika tidak ada siapa-siapa.
Namun pada hari wisuda, hari yang seharusnya menjadi pengakuan atas perjuangan itu, nama ibu sering kali tidak disebut. Ia absen dari panggung simbolik. Yang hadir justru nama ayah — bahkan ketika ayah itu tidak pernah hadir dalam kehidupan anaknya, atau justru menjadi sumber luka.
Inilah wajah patriarki simbolik yang masih dipertahankan dalam ritual akademik. Bukan patriarki yang kasar dan terang-terangan, melainkan patriarki yang bekerja halus melalui bahasa dan tradisi. Ia dinormalisasi, diwariskan, dan jarang dipertanyakan.
Padahal dunia pendidikan hari ini kerap menggaungkan nilai inklusivitas, kesetaraan gender, dan kepedulian terhadap kesehatan mental. Kampus berbicara tentang mahasiswa sebagai subjek yang utuh. Namun pada momen wisuda, kampus justru menghapus keutuhan itu dengan satu asumsi tunggal tentang keluarga.
Wisuda seharusnya menjadi ruang penghargaan atas kerja intelektual, ketekunan, dan daya tahan mahasiswa. Bukan arena pemaksaan narasi keluarga yang seragam. Ketika bahasa yang digunakan kampus justru memicu kecemasan, trauma, bahkan C-PTSD, maka ada yang salah dalam cara kita memaknai tradisi.
Pertanyaannya sederhana: mengapa kampus tidak bertanya? Mengapa tidak memberi pilihan kepada mahasiswa, ingin disebut anak dari ayah, ibu, atau cukup namanya sendiri? Pilihan ini tidak mengurangi kehormatan wisuda. Tidak merusak tata protokol. Justru menunjukkan kedewasaan institusi dalam menghargai keberagaman jalan hidup.
Pilihan penamaan adalah bentuk pengakuan identitas. Memberi pilihan berarti mengakui bahwa mahasiswa adalah subjek dengan pengalaman hidup yang sah, bukan objek tradisi yang harus patuh tanpa suara.
Bagi sebagian mahasiswa, wisuda hari ini meninggalkan kenangan yang terasa ternoda. Bukan karena mereka gagal, tetapi karena sistem tidak memberi ruang bagi kenyataan hidup mereka. Pencapaian akademik yang seharusnya membanggakan justru diselimuti rasa perih yang sulit dijelaskan.
Tulisan ini bukan serangan terhadap ayah sebagai figur. Banyak ayah yang hadir, berjuang, dan layak dihormati. Namun sistem pendidikan tidak boleh memaksakan satu narasi untuk semua. Menghormati ayah tidak harus dilakukan dengan menghapus ibu, atau menutup mata terhadap luka anak.
Sudah saatnya kampus, sekolah, Dinas Pendidikan, dan Dikti memerhatikan praktik simbolik yang selama ini dianggap sepele, dalam beberapa pemanggilan nama saat wisuda atau juga penulisan nama di ijazah sekolah. Bahasa yang digunakan institusi pendidikan harus berpihak pada kemanusiaan, bukan sekadar melestarikan tradisi.
Pejuang-pejuang psikis ada di ruang kelas kita. Mereka lulus bukan karena hidup ramah, tetapi karena mereka bertahan. Mereka layak mendapatkan wisuda yang menyembuhkan, bukan yang melukai.
Wisuda seharusnya meninggalkan rasa dihargai sepenuhnya: lahir dan batin wisudawan. Karena bahasa tidak pernah netral. Setiap penyebutan “anak dari Bapak X” atau “anak dari Ibu Y” selalu membawa pengalaman hidup di belakangnya: ada yang merasa bangga, ada yang justru terluka. Itulah sebabnya tindak tutur kampus semestinya tidak seragam, melainkan memberi pilihan kepada wisudawan — ingin menyebut ayah, ibu, keduanya, atau cukup namanya sendiri. Bahkan di sejumlah kampus di Malaysia, nama orang tua tidak disebut sama sekali; mahasiswa cukup dipanggil namanya. Sederhana, tetapi adil.
Jika pendidikan sungguh ingin memanusiakan manusia, sudah saatnya kampus meninggalkan sistem patriarki yang usang dan berhenti memaksakan satu narasi keluarga. Wisuda harus menjadi ruang kebanggaan yang utuh, bukan seremoni yang tanpa sadar mengulang luka. (*_Penulis adalah linguis dan jurnalis_)