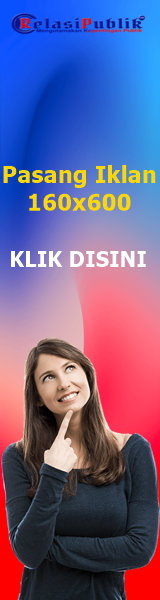Oleh : Domi Kani
Di setiap bencana, kita selalu menyaksikan dua hal yang berjalan berdampingan: kesedihan yang dalam, dan solidaritas yang menghangatkan. Namun di antara arus kepedulian itu, masih ada satu fenomena yang seharusnya kita renungkan bersama—bantuan berupa pakaian bekas yang tak lagi layak pakai.
Bukan soal menolak uluran tangan. Para relawan pun tahu, setiap pemberian lahir dari keinginan membantu. Tetapi di lapangan, ada rasa sungkan yang membuat mereka tak kuasa berkata jujur. Tak enak menolak, tak sanggup pula menyampaikan bahwa sebagian pakaian itu justru menambah beban alih-alih meringankan.
Karena kenyataannya, bencana bukan tempat bagi barang-barang yang telah lama tak kita pakai. Bencana adalah ruang darurat, tempat orang kehilangan rumah, kehilangan pegangan, bahkan kehilangan harapan. Di tengah rapuhnya kondisi itu, mereka layak menerima bantuan yang memulihkan martabat—bukan sisa lemari yang tak lagi dipakai di hari baik.
Relawan bekerja tanpa henti, namun harus pula memilah pakaian yang robek, lusuh, bahkan tak layak pakai. Ketika tenaga seharusnya fokus pada penyelamatan dan pendistribusian, mereka malah terbebani oleh barang-barang yang semestinya tidak dikirim sejak awal.
Di sinilah empati kita diuji. Ketulusan tidak hanya diukur dari kuantitas bantuan, tetapi kualitas kepedulian. Memberi bukan soal apa yang ingin kita singkirkan, melainkan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh mereka yang sedang berjuang bangkit.
Masyarakat yang terdampak bencana bukan penerima sembarangan. Mereka adalah manusia yang sedang melewati masa paling sulit, dan karenanya berhak atas bantuan yang menghormati martabat mereka.
Mungkin sudah saatnya kita bertanya pada diri sendiri: Apakah bantuan ini bermanfaat? Apakah layak? Apakah saya akan memakai ini jika saya berada dalam posisi mereka?
Jika jawabannya ragu, mungkin kita sudah tahu apa yang harus dilakukan.
Solidaritas adalah bahasa kemanusiaan. Mari menyampaikannya dengan cara yang benar.