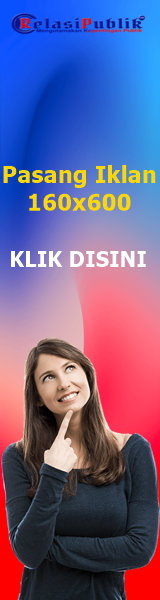Oleh : Muhammad Alfarez
Ilmu Politik Universitas Andalas
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) adalah organisasi kader mahasiswa yang lahir pada 23 Maret 1954. Ideologi GMNI didasarkan pada nasionalisme dan Marhaenisme ajaran Bung Karno yang menentang penindasan dan memperjuangkan hak-hak rakyat tertindas. Dalam konteks ini, nama Sarinah yang diambil dari buku Bung Karno (1947) menjadi simbol penting dalam kebudayaan organisasi GMNI. Sarinah awalnya adalah sosok pengasuh Bung Karno yang menjadi inspirasi berpikirnya tentang peran perempuan dan rakyat kecil. Pada Rakernas GMNI 1977 ditetapkan bahwa kader perempuan dipanggil “Sarinah”, sedangkan kader laki-laki “Bung” suatu penghargaan khusus yang terinspirasi dari kisah Bung Karno. Tulisan ini mengkaji bagaimana gagasan-gagasan Bung Karno dalam buku Sarinah mempengaruhi ideologi, strategi kaderisasi, dan praksis gerakan sosial GMNI. Selain itu dianalisis bagaimana GMNI menafsirkan konsep “Sarinah” sebagai simbol perjuangan kaum perempuan dan rakyat tertindas dalam konteks sejarah maupun masa kini, menggunakan kerangka teori feminis, teori gerakan sosial, dan Marhaenisme.
Sejarah pemikiran Sarinah dimulai saat Bung Karno mengabadikan nama pengasuhnya pada buku tentang peran perempuan dalam pembangunan bangsa. Dalam buku itu, Sukarno menegaskan bahwa “soal wanita” esensial karena “tidak dapat menyusun negara dan masyarakat jika tidak mengerti soal wanita”. Pernyataan terkenal Sukarno bahwa “Perempuan itu tiang negeri manakala baik perempuan, baiklah negeri” mencerminkan betapa sentralnya posisi wanita dalam revolusi nasional. Konsep Sarinah menurut sukabudi ini adalah yang memuat nilai feminisme sosialis, yaitu hak-hak perempuan dalam keluarga, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial. Namun, beberapa studi kritis mencatat dualisme pandangan Sukarno meski memuliakan peran perempuan, ia tetap berada dalam kerangka patriarki dan menolak konsep feminis radikal.
Di ranah gerakan mahasiswa, GMNI lahir dari peleburan organisasi berideologi Marhaen dan nasionalis. Marhaenisme Bung Karno varian Marxisme lokal menekankan perjuangan bersama kaum terhimpit melawan kapitalisme dan imperialisme. Landasan Marhaenisme inilah yang menempatkan Sarinah sebagai simbol perjuangan kaum “orang kecil” (rakyat jelata) maupun simbol perjuangan perempuan dalam semangat revolusioner Bung Karno. Dalam kajian feminis, gerakan Sarinah Bung Karno dipandang sebagai upaya mengintegrasikan isu gender ke dalam Revolusi Nasional Indonesia. Sedangkan dari perspektif teori gerakan sosial, GMNI merupakan contoh aksi kolektif yang menggunakan simbol ideologis (frame) untuk memobilisasi massa mahasiswa dalam agenda perubahan sosial.
Pertama, gagasan Sarinah Bung Karno secara langsung mempengaruhi ideologi dan simbolisme internal GMNI. GMNI menempatkan diri sebagai organisasi perjuangan rakyat kecil sesuai Marhaenisme, sehingga tokoh Sarinah perempuan desa yang mendidik Sukarno mencintai rakyat dijadikan panutan. Dalam materi kader GMNI bahkan dijelaskan bahwa “Sarinah mengajari Soekarno untuk mencintai rakyat (orang kecil)”. Sejalan itu, buku Sarinah Bung Karno yang berisi soal perempuan digunakan sebagai rujukan untuk menyeimbangkan peran laki-laki dan perempuan dalam perjuangan sosial.
GMNI mengkaitkan gelar “Sarinah” dengan perempuan pejuang kader perempuan GMNI berhak dipanggil Sarinah di depan nama mereka, mengangkat status simbolik perempuan aktivis setara dengan Sukarno yang disebut “Bung”. Hal ini sejajar dengan ide feminisme yang menekankan kesetaraan gender. Menurut Kabid Keorganisasian GMNI, penggunaan nama “Sarinah” juga dimaksudkan agar kader perempuan dapat menunjukkan kemerdekaan dan keputusan sendiri, mencerminkan semangat Kartini Sukarno dalam pemberdayaan wanita.
Kedua, dalam strategi kaderisasi GMNI memasukkan konsep Sarinah ke dalam kurikulum ideologi. Materi PPAB (Pelatihan Pembentukan Anggota Baru) GMNI memuat “Pengantar Sarinah” untuk menjelaskan sejarah perjuangan perempuan menurut Bung Karno. Analogi sayap burung dalam pandangan GMNI menegaskan peran kerja sama gender “perempuan dan laki-laki ibarat sepasang sayap jika keduanya berjalan beriringan maka dunia baru yang dicita-citakan kaum marhaenis akan tercapai”. Ini meneguhkan pemahaman Marhaenisme bahwa revolusi sosial adalah perjuangan kolektif semua golongan, termasuk perempuan sebagai agen revolusi.
Dalam pandangan teori gerakan sosial, hal ini berfungsi sebagai frame bersama (collective frame) untuk merekrut anggota dan mengarahkan praktik advokasi. GMNI juga melibatkan “Sarinah” dalam organisasi aksi sosial-massa misalnya pada peringatan Hari Kartini, DPC GMNI Kuningan menggelar aksi bertema Perempuan adalah Pejuang untuk membangkitkan kesadaran politik perempuan. Kegiatan semacam ini memperlihatkan praktik gerakan sosial GMNI yang secara eksplisit mengaitkan isu gender dengan perjuangan rakyat. Dari perspektif teori gerakan sosial GMNI memobilisasi sumber daya (kader, literasi ideologi, orasi, media) di bawah simbol Sarinah untuk menuntut perubahan sosial (misalnya advokasi kesetaraan gender dalam pendidikan dan pekerjaan).
Ketiga, Sarinah sebagai simbol merepresentasikan perjuangan perempuan dan rakyat tertindas dalam konteks historis dan kontemporer. Secara historis, Bung Karno menulis Sarinah pada 1947 untuk menegaskan bahwa kemerdekaan bangsa takkan utuh tanpa partisipasi aktif perempuan. GMNI, sebagai pewaris ideologi Bung Karno, menggunakan figur Sarinah untuk meresapi kesadaran kelas (rakyat kecil) dan gender. GMNI memaknai Sarinah tidak hanya sebagai nama (sapaan) tetapi sebagai panggilan revolusioner perempuan dalam GMNI dituntut menjadi “progresif-revolusioner” dan ikut andil bersama laki-laki dalam menyelesaikan persoalan bangsa.
Menurut teori feminis, hal ini menunjukkan sisi normatif kesetaraan gender namun kritik internal dari pemikiran feminis sosialis mencatat bahwa GMNI seringkali terjebak pada relung patriarki Sukarno dalam prakteknya, mahasiswa GMNI cenderung masih terpaku pada pemikiran Bung Karno yang relatif konservatif soal gender sebagai contoh, penelitian Firda dan kolega (2023) menemukan bahwa kader Sarinah GMNI masih menginternalisasi pemikiran Sukarno yang tidak menantang struktur patriarki keluargaresearchgate.net. Hal ini menunjukkan kontradiksi antara simbolik penggunaan Sarinah sebagai inspirasi feminis-revolusioner dengan realitas organisasi yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip feminis progresif.
Dari sudut Marhaenisme, Sarinah juga melengkapi narasi perjuangan rakyat kecil. Bung Karno sendiri mendapat inspirasi cinta pada rakyat jelata dari figur Sarinah. Dalam ideologi marhaen, “Marhaen” adalah petani tertindas yang memiliki alat produksi sendiri tapi tidak cukup untuk bertahanid. GMNI menerjemahkan Sarinah sebagai marhaen perempuan ia perempuan desa yang sederhana namun mempunyai semangat membela rakyat. Dengan demikian, simbol Sarinah menyinergikan perjuangan kelas dengan pengakuan atas peran gender ia mewujudkan sosok rakyat kecil (kelas bawah) sekaligus ibu pejuang.
Pendekatan gerakan sosial dan feminis menyarankan agar simbol semacam ini menjadi bahan framing emansipatoris dalam agenda organisasi.
Gagasan Sarinah Bung Karno telah menjadi bangunan simbolik penting bagi GMNI sebagai gerakan sosial. Melalui ideologi Marhaenisme yang diambil dari ajaran Sukarno, GMNI mengangkat Sarinah sebagai lambang kesetaraan gender dan solidaritas terhadap rakyat terpinggirkan. Konsep ini tercermin dalam struktur organisasi GMNI (sapaan “Bung” dan “Sarinah”) serta dalam kurikulum kaderisasi yang menekankan peran perempuan sebagai “sayap” revolusi. Namun analisis teoritis mengingatkan bahwa internasalisasi nilai feminis-sosialis di kalangan kader belum optimal. Oleh karena itu, seruan praktis bagi GMNI adalah menerjemahkan semangat Sarinah dalam kebijakan nyata misalnya, mendorong lebih banyak perempuan memegang posisi strategis, membumikan agenda gender-equality dalam advokasi kebijakan publik, serta mengadakan pelatihan kader berbasis pemikiran marhaen-feminis. Dengan begitu, Sarinah tidak hanya menjadi nama simbolis, tetapi juga implementasi konkret dari cita-cita pro-rakyat dan emansipasi kaum perempuan yang diwariskan Bung Karno.