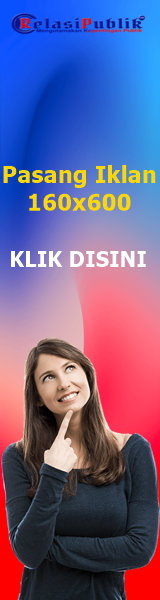Oleh : Yolla Nabila Fahepy, Cindi Gustrianita, M. Jovan Fadlal, Paska Agave Angelita, dan Alqoury Muhammad Farhan
Mahasiswa FISIP Unand
Militer di sebut sebagai kekuatan politik di Indonesia. Hal tersebut karena secara historis dan struktural, militer tidak hanya sekedar alat pertahanan semata, melainkan juga memainkan peranan sentral dalam proses politik dan pemerintahan. Akar dari kekuatan politik militer bersumber dari adanya fenomena Dwi Fungsi ABRI di masa Orde Baru. Era di mana tercatatnya sejarah peran ganda militer, di mana tidak hanya terlibat di bidang pertahanan-keamanan, melainkan juga di bidang sosial-politik. Dalam praktiknya, doktrin inilah yang mentransformasikan TNI menjadi salah satu pilar utama kekuasaan, di mana jenderal-jenderalnya menduduki pos-pos strategis di kabinet, parlemen, birokrasi, dan BUMN. Warisan inilah yang membentuk DNA politik militer di Indonesia, di mana militer boleh memiliki jaringan, sumber daya, dan legitimasi untuk terus terlibat dalam percaturan kekuasaan.
Reformasi 1998 menandai babak baru dalam sejarah Indonesia dengan mendepolitisasi militer sebagai agenda utamanya. Dwi Fungsi ABRI yang selama 32 tahun mengakar di kekuasaan Orde Baru secara resmi dicabut. TNI yang kemudian menggantikan ABRI dikembalikan ke fungsi utamanya yaitu sebagai alat pertahanan negara, sebuah institusi yang netral dari politik praktis. Namun, lebih dari dua dekade pasca-Reformasi, sebuah dinamika yang mengkhawatirkan terjadi. Ancang-ancang kembalinya militer ke dalam ranah politik dan sipil semakin nyata. Tercermin dari revisi UU TNI dan mulai menyebarnya perwira TNI dalam menggerogoti jabatan sipil. Hal ini bukan hanya menyalahi tutuntan Reformasi, tetapi juga menggerus fondasi demokrasi yang telah diperjuangkan.
Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI belakangan menuai kontroversi. Meski secara resmi bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara, namun sejumlah pasal dalam RUU tersebut berpotensi mengembalikan TNI ke panggung politik. Salah kritiknya adalah adanya perluasan peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Meski terlihat teknis, definisi OMSP yang terlalu luas dan multitafsir dapat menjadi celah bagi TNI untuk terlibat dalam urusan sipil.
Misalnya, keterlibatan dalam penanganan konflik sosial, bencana alam, atau bahkan masalah pangan dapat dengan mudah bergeser menjadi intervensi politik. Dalam sistem demokrasi yang sehat, fungsi-fungsi semacam ini adalah domain pemerintah sipil, kepolisian, dan institusi publik lainnya. Ketika TNI masuk dengan logika dan komando militernya, terjadi militerisasi kehidupan sipil yang melunturkan supremasi hukum sipil.
Praktik penempatan perwira aktif atau purnawirawan TNI dalam jabatan-jabatan sipil semakin marak. Posisi seperti menteri, kepala BUMN, gubernur, hingga bupati menjadi incaran. Praktik ini adalah bentuk nyata dari Dwi Fungsi ABRI era rezim orde baru. Meski dilakukan melalui mekanisme pengangkatan dan bukan penugasan formal oleh institusi TNI, efeknya sama, logika dan jaringan militer menguasai arena politik dan ekonomi. Hal ini tentu menyalahi semangat dan aturan Reformasi. TAP MPR No. VI/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI serta TAP MPR No. VII/2000 tentang Peran TNI dan POLRI telah menegaskan kembali netralitas TNI. Dengan menduduki jabatan sipil, seorang perwira secara de facto telah melanggar prinsip netralitas tersebut. Hal ini seperti membawa loyalitas dan hierarki militer ke dalam pemerintahan yang seharusnya dijalankan dengan prinsip akuntabilitas publik dan kompetisi politik yang sehat.
sejarah politik global memberikan bukti yang gamblang bahwa negara-negara yang melegalkan atau membiarkan militer mendominasi urusan pemerintah cenderung mengalami kegagalan dalam membangun tata kelola yang baik dan sejahtera. Di negara-negara tersebut, dominasi militer hampir selalu berujung pada pemerintahan yang otoriter, tertutup, dan represif. Logika komando yang kaku dan hierarkis, yang efektif di medan perang, terbukti gagal ketika diterapkan untuk mengelola ekonomi yang kompleks, pelayanan publik, atau dinamika sosial masyarakat yang plural. Bukannya menciptakan stabilitas, model pemerintahan militer justru mematikan inovasi, memberangus kebebasan berekspresi, dan seringkali menyuburkan korupsi yang terstruktur karena kurangnya pengawasan dan akuntabilitas publik. Investasi dan kepercayaan internasional pun biasanya enggan masuk ke dalam lingkungan yang tidak demokratis dan penuh ketidakpastian. Dengan demikian, melibatkan militer dalam pemerintahan sipil bukan hanya berisiko terhadap demokrasi, tetapi juga merupakan resep yang terbukti gagal untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Alasan lain mengapa TNI tidak boleh terlibat dalam urusan sipil dalam sebuah negara demokrasi terletak pada ketimpangan legitimasi dan kekuatan yang fundamental. Dalam pelaksanaan demokrasi, kekuasaan berasal dari rakyat dan dijalankan untuk rakyat oleh pemerintah sipil yang mereka pilih. Sementara itu, TNI yang dibiayai oleh uang rakyat dibekali dengan persenjataan lengkap dan pelatihan tempur yang mematikan dengan satu mandat tunggal, mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman eksternal. Ketika institusi dengan monopoli atas alat-alat kekerasan fisik ini masuk ke dalam ranah pemerintahan sipil, maka keseimbangan yang rapuh ini langsung runtuh. Kekuasaan tidak lagi bersumber pada suara rakyat, tetapi pada ancaman dari kekuatan senjata. Kekhawatiran tentang kudeta bukanlah sekadar teori konspirasi karena dalam situasi di mana militer memiliki pengaruh politik yang besar dan merasa kepentingannya terganggu, godaan untuk menggunakan kekuatan fisik untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan menjadi sangat nyata. Dalam skenario terburuk tersebut, rakyat sipil yang hanya bersenjatakan hak pilih dan suara protes akan berada dalam posisi yang sangat lemah dan tidak berdaya menghadapi organisasi yang terlatih dan bersenjata lengkap, sehingga cita-cita kedaulatan rakyat pun hanya menjadi ilusi.
Sederhananya, dinamika ini menunjukkan bahwa perjuangan Reformasi belum selesai. Pencabutan Dwi Fungsi ABRI secara formal ternyata tidak cukup. Kini Indonesia kembali merasakan pengaruh militer melalui cara-cara yang lebih halus dan terinstitusionalisasi, seperti revisi UU yang bermasalah dan penguasaan jabatan sipil contohnya. Jika dibiarkan, hal ini akan menggerogoti demokrasi Indonesia dari dalam. Fenomena ini seakan menjadi tamparan mengenai dipeerlukannya kewaspadaan kolektif dari seluruh elemen bangsa parlemen, pers, akademisi, dan masyarakat sipil untuk terus mendorong konsistensi pada agenda reformasi sektor keamanan. TNI harus tetap menjadi penjaga kedaulatan negara di garis depan, bukan menjadi kekuatan politik yang menentukan arah pemerintahan. Mengembalikan TNI sepenuhnya ke barak bukan berarti melemahkannya, justru itu adalah cara untuk memuliakan profesinya dan memperkuat demokrasi kita yang masih terus belajar berdiri tegak.