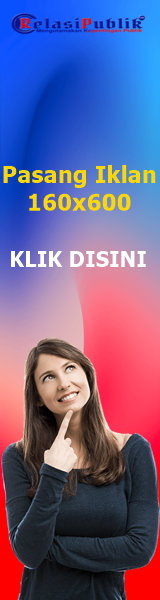Oleh: Musfi Yendra
Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
Sumbar,relasipublik – Akses terhadap informasi bukan sekadar kebutuhan, melainkan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia, di era demokrasi yang semakin terbuka. Dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
Hal ini menandakan bahwa informasi bukan lagi milik eksklusif negara, melainkan hak konstitusional seluruh warga. Di sinilah letak pentingnya keterbukaan: negara tidak lagi menjadi satu-satunya pemegang kendali atas informasi publik, tetapi berkewajiban menyediakannya untuk kepentingan bersama.
Pengakuan terhadap hak atas informasi juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
Jaminan ini tidak hanya mengafirmasi prinsip-prinsip konstitusi, tetapi juga menempatkan keterbukaan informasi sebagai prasyarat utama tercapainya keadilan sosial. Tanpa akses informasi yang merata, masyarakat tidak memiliki cukup alat untuk memperjuangkan hak pendidikan, layanan kesehatan, ataupun keadilan ekonomi.
Dalam praktik kenegaraan, semangat konstitusi dan prinsip-prinsip HAM tersebut diterjemahkan lebih teknis melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang ini hadir sebagai instrumen hukum untuk memastikan bahwa setiap badan publik wajib memberikan akses informasi kepada masyarakat.
Melalui UU KIP, hak atas informasi menjadi hak yang dapat dituntut secara hukum. Setiap badan publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melayani permintaan informasi secara cepat, tepat, dan sederhana. Tidak hanya itu, masyarakat juga diberi ruang untuk menggugat jika informasi yang diminta tidak diberikan atau ditolak secara sepihak.
UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi publik, mulai dari informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, hingga informasi yang wajib tersedia setiap saat. Dengan pengklasifikasian ini, UU KIP tidak hanya mendorong keterbukaan, tetapi juga membentuk mekanisme kontrol dan evaluasi terhadap badan publik.
Dalam konteks inilah, Komisi Informasi menjadi lembaga strategis yang berperan mengawal dan menyelesaikan sengketa keterbukaan informasi antara masyarakat dan badan publik.
Sebagai tindak lanjut dari UU KIP, Komisi Informasi juga mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi (Perki), antara lain Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Perki ini menjadi panduan teknis yang mengatur tata cara pelayanan informasi publik di seluruh badan publik.
Mulai dari mekanisme permintaan informasi, format layanan, waktu pemberian respons, hingga kewajiban proaktif badan publik dalam menyediakan informasi. Perki ini juga memberikan perhatian khusus terhadap kelompok rentan—seperti masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan warga di daerah terpencil—agar hak mereka atas informasi tidak terabaikan.
Dalam sistem demokrasi yang sehat, keterbukaan informasi adalah syarat utama. Informasi adalah fondasi dari partisipasi publik. Tanpa informasi, rakyat tidak dapat mengawasi kebijakan, mengevaluasi kinerja pejabat, atau ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan.
Sebaliknya, ketika informasi dibuka, partisipasi meningkat, kepercayaan publik tumbuh, dan risiko penyalahgunaan kekuasaan dapat ditekan. Transparansi menciptakan ruang dialog antara pemerintah dan rakyat yang selama ini sering tersumbat oleh birokrasi yang tertutup.
Namun demikian, implementasi keterbukaan informasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Tidak semua badan publik siap dan terbuka dalam menyajikan informasi. Masih banyak ditemukan PPID yang belum menjalankan fungsinya dengan baik, informasi yang tidak tersedia secara berkala, serta mentalitas birokrasi yang masih melihat informasi sebagai sesuatu yang harus dilindungi, bukan dibagikan.
Bahkan, dalam beberapa kasus, permohonan informasi masih dianggap sebagai bentuk ancaman, bukan hak warga yang dijamin undang-undang. Ketimpangan akses antara kota dan desa juga menjadi masalah tersendiri, apalagi di wilayah-wilayah dengan infrastruktur digital yang terbatas.
Namun harapan tetap menyala. Kesadaran publik terhadap hak atas informasi terus meningkat. Media massa, LSM, akademisi, dan masyarakat sipil mulai aktif menggunakan hak ini sebagai instrumen pengawasan.
Komisi Informasi di berbagai daerah juga terus melakukan edukasi, advokasi, dan mediasi untuk memperkuat budaya keterbukaan. Teknologi informasi turut mendukung, membuka akses yang lebih luas dan cepat, bahkan hingga ke pelosok negeri.
Informasi adalah kekuatan, dan dalam negara demokrasi, kekuatan itu harus dimiliki oleh rakyat. Menjadikan informasi sebagai hak asasi adalah bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan menjamin keterbukaan, kita bukan hanya membangun pemerintahan yang transparan, tetapi juga masyarakat yang kritis, sadar hak, dan aktif membangun masa depan.
Keterbukaan informasi bukan semata soal legalitas, tetapi juga etika dan moral dalam melayani rakyat. Karena itu, mari terus kawal dan perjuangkan hak atas informasi sebagai bagian dari cita-cita reformasi dan demokrasi yang berkeadilan. []